Dr. Paul Budi Kleden
DUA SUASANA berbeda mewarnai dua perayaan terbesar orang Kristen, Natal dan Paskah. Kalau Natal ditandai oleh gemerlap pusat-pusat perbelanjaan, Paskah cukup sepi dari hiruk pikuk komersial. Jika Natal telah merasuk ke benak umum dan menjadi perayaan kemasyarakatan, Paskah merupakan perayaan keagamaan yang hanya diamaknai oleh umat Kristen. Tidak ada Paskah bersama yang dirayakan secara nasional dan ditayangkan berbagai stasiun televisi. Apabila Natal terancam kehilangan intinya karena tendensi eksteriorisasi makna religius, Paskah justru terancam ketiadaan daya tarik karena kuatnya konsentrasi pada makna religius. Memang kita lebih mudah tersentuh untuk merayakan kehidupan, daripada berkutat dengan tema kematian; kita lebih tergugah oleh kehadiran seorang bayi daripada tubuh seorang lelaki dewasa di atas salib atau di hadapan kubur yang terbuka. Paskah memang bukan peristiwa untuk membangkitkan perasaan, dan pesannya tak gampang dicerna pikiran.
Tuhan tidak perlu ke Utopia
Keyakinan akan adanya hidup setelah kematian bukan baru sekarang terasa sulit diterima. Yang sulit menerima keyakinan ini bukan hanya orang tidak beriman. Di kalangan bangsa Yahudi yang teguh beriman pada masa Yesus pun sudah ada kelompok orang beragama yang merasa tidak ada alasan yang cukup dan mendesak untuk menerima akan adanya kehidupan setelah kematian. Mereka disebut kaum Sadduki. Mereka yakin, bahwa hidup hanya sekali dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Dunia adalah satu-satunya tempat untuk mendapatkan kebahagiaan. Di bumi ini segalanya berlangsung. Tidak ada hidup yang lain. Kalau ada pahala untuk kebaikan yang pernah dilakukan, atau pembalasan untuk kejahatan yang pernah terjadi, itu akan dialami oleh generasi yang menyusuli. Dunia dan sejarah sudah cukup untuk menjelaskan kebaikan dan keburukan, kebahagiaan dan penderitaan.
Hanya orang yang sedang bermimpi berbicara tentang hidup setelah kematian. Pembicaraan seperti ini hanya membuang waktu dan tidak pernah bisa dipandang penting. Kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, maka kebangkitan orang mati pun tidak ada dasarnya. Kebangkitan lalu menjadi sebuah utopia. Dan memang Paskah berkaitan dengan utopia.
Dalam novelnya “Wir sind Utopia”, (Kita adalah Utopia), Stefan Andres (1906-1970), seorang sastrawan Jerman melukiskan kisah petualangan seorang mantan rahib Katolik di Spanyol pada masa kekuasaan diktator Franco Paco Gonsalves, demikian nama tokoh utama itu. Dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan di biara dan melibatkan diri dalam perjuangan rakyat yang sedang memberontak melawan Franco. Namun, akhirnya dia ditangkap dan kemudian justru ditawan di dalam biaranya dahulu. Di sana, ia teringat kembali akan impiannya saat masih sebagai rahib muda di biara itu. Dia berkhayal seolah sedang melihat Utopia, pulau impiannya, dari balik jendela kamarnya. Masih dalam khayalan, dia memandang dirinya berlayar ke pulau itu, berulang kali.
Pada suatu hari dia mendapat kesempatan berbicara dengan seorang mantan gurunya, Pastor Damiano. Dia berbicara juga tentang pulau itu dan kerinduannya yang tak terbendung untuk ke sana. Pastor Damiano menasihati: “Jangan lagi engkau pergi ke pulau itu. Engkau tidak pernah boleh lupa, bahwa tidak seorang pun telah berhasil mengubah dunia menjadi sebuah utopia. Tuhan pun tidak! Consalves, jika engkau sadar bahwa seluruh dunia adalah satu pasar bursa (Pastor Damiano pernah menjadi seorang pemilik bank yang berhasil dan disegani), dan apabila engkau melihat betapa rendahnya nilai saham Tuhan yang engkau tetap mau beli, maka dalam hati pasti engkau sebenarnya berpikir: siapa tahu apa yang terjadi? Siapa tahu saham ini kemudian bernilai kembali? Saya bisa langsung katakan kepadamu bahwa engkau sedang berspekulasi dan spekulasimu sama sekali meleset. Nilai saham itu terus melorot pada saat engkau sedang membelinya……..Sebab itu engkau dilihat dan dinilai sebagai orang tolol, dan banyak orang menertawkanmu. …..Keajaiban terbesar adalah masih percaya pada saham yang bermasalah itu, bukan karena itu tertulis sebagai perintah Tuhan, melainkan suara hati kita sendiri berbisik bahwa saham ini memang asli. Inilah jalan, kebenaran dan kehidupan…….Sebab itu jadilah setia dan jujur, percaya, berharap dan terutama hiduplah dalam kasih. Dan saham yang engkau pegang itu jauh lebih memperkaya engkau daripada sebuah utopia. ……Tuhan tidak pergi ke Utopia – Dia datang ke bumi yang dipenuhi air mata ini, berulang kali!” (1). Ya, Tuhan tidak pernah ke Utopia, tetapi Dia datang ke bumi, sebab di sini, di tengah kemiskinan yang tragis ini, dalam bencana kelaparan yang menghantui, di tengah lembah penderitaan yang kelam, Dia hadir sebagai harapan yang menentang kemapanan, ya sebagai utopia.
Kita butuh Utopia
Tampaknya, manusia selalu memerlukan utopia, sebuah dunia yang diimpikan dan dirindukan. Namun, ada dua bahaya yang selalu muncul berhadapan dengan utopia. Di satu pihak, utopia sering dilihat sebagai tempat pelariaan dari kenyataan yang keras dan menantang. Tak mampu berhadapan dengan dunia dan sejarah seperti ini, orang lari ke dunia utopia. Di sini, utopia seumpama opium yang melumpuhkan daya ubah. Pada pihak lain, utopia dapat menjadi ideologi yang memaksa. Utopia dipandang sebagai imperative yang tidak mengenal kompromi.
Yang utopis memang merupakan yang ideal. Namun dia tidak secara niscaya berarti tidak realistis. Dia muncul dari relitas dan kembali menjadi roh bagi perubahan di tengah situasi konkret. Sebenarnya utopia adalah sebuah kritik atas kenyataan dan sangguo menggerakkan perubahan di tengah kenyataan. Utopia pun bukan pertama-tama rekaan manusia. Dalam bingkai iman, sebagaimana dikatakan Stefan Andres dalam novelnya, utopia itu datang dari Tuhan. Tuhan datang, karena itu manusia pun dapat bertransformasi. Gerakan pembebasan masyarakat selalu berkait dengan utopia tertentu. Sebab itu, utopia pun selalu bermuatan politis, berdaya gugat terhadap status quo dan berkemampuan ubah terhadap kondisi aktual.
Mereka yang mempertahankan kemapanan sebenarnya tidak lagi menghendaki kehidupan. Tidak jarang ambisi ini diwujudkan dengan memumifikasi diri sendiri dalam bentengnya dan menghancurkan kehidupan orang lain. Mereka menumpulkan perasaannya dari persentuhan dengan orang lain. Empati disejajarkan dengan kelemahan dan kekalahan. Orang kehilangan perhatian dan mengalami kematian perasaan. Maka solidartas pun mengalami defisit yang serius. Pikirannya direduksi menjadi kelicikan untuk memperkaya dan mengamankan diri. Kecerdasan adalah soal menyusun strategi untuk selalu tampil sebagai pemenang tanpa peduli apa dan berapa ongkosnya. Yang mesti roboh dan rebah pada pentas persaingan dinilai sebagai bodoh atau sedang bernasib sial.
Oleh dan atas nama kuasa kemapaman Yesus telah dibunuh. Yang diberitakan-Nya dinilai terlalu berbahaya bagi keamanan para penguasa agama dan politik. Dia berbicara tentang Tuhan yang menjadi pembela para miskin dan tertindas. Bapa para pendosa dan sahabat mereka yang terbuang. Dia menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin, baik di dalam agama pun dalam politik. Agama tidak hidup dari hukum mengeksklusi kelompok orang tertentu tapi dari kesediaan untuk memberi ampun. Politik bukanlah soal kelicikan merampas hak pihak lain, melainkan kesanggupan untuk memberi kepada kaiser apa yang menjadi hak Kaiser, dan kepada Tuhan apa yang sesungguhnya menjadi hak Tuhan. Tak pantas kaiser merebut hak Tuhan dan bertindak absolut seolah dia adalah yang ilahi. Logika agama dan kerangka berpikir politik seperti ini memang sangat mudah mengantar seorang tokoh pembaru ke tiang gantungan.
Pada latar seperti ini, kebangkitan berarti Tuhan sendiri menghadirkan diri sebagai utopia, sebagai dunia yang semestinya dan menjadi hak manusia. Utopia yang dibawanya bukanlah mimpi yang mengantar manusia pergi dari dunianya, menghanyutkan dalam halusinasi yang mengalienasi. Paskah, kebangkitan menunjukkan bahwa Tuhan adalah perubahan. Tuhan tidak dapat dikuburkan dan dibungkamkan, dan Dia pun tidak rela membiarkan manusia terus dikuburkan dalam penjara ketakutan dan dibungkamkan oleh para penguasa.
“Tuhan adalah sebuah kata kerja”, kata Kurt Marti, seorang teolog Protestan berkebangsaan Swiss (2). Kata kerja berarti keaktifan. Tuhan bukan nama lain dari kematian dan kepasrahan. Kematian karena bencana kelaparan bukanlah sesuatu yang terjadi di bumi yang dihuni manusia yang beradap. Keterbelakangan karena pembodohan yang sistematis tidak pernah dapat dilihat sebagai nasib yang tergaris pada tangan manusia yang berpikir.
Paskah adalah sebuah perayaan yang secara radikal menuntut perubahan. Tidak adalagi kubur yang secara abadi sanggup menyimpan kebohongan dan penipuan. Mengandalkan represi sebagai sarana untuk pembungkaman kebenaran tidak akan pernah bertahan selamanya. Paskah adalah sebuah perubahan radikal, bukan sekedar reformasi. Paskah pun mesti menggerakkan perubahan itu. Mungkin karena itu Paskah tidak dapat di komersialisasi, wartanya tidak mudah direkam. Perayaan ini pun kurang diminati. Paskah bukanlah perayaan untuk mereka yang tenggelam dalam kemapanan dan bersekongkol dengan kuasa kematian.
Persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa yang terus dililit masalah seperti bangsa kita adalah ketiadaan harapan, kehilangan utopia. Kita menjadi sulit percaya akan rencana dan pada kemungkinan perubahan. Rentetan bencana ternyata tak pernah sanggup membuat kita belajar mengantisipasi. Setiap tahun kita selalu dikejutkan oleh persoalan yang sama tentu bukanlah satu tanda keterpelajaran. Program-progam pembangunan lebih pantas disebut sebagai program penetesan ke bawah setelah pusat-pusat pengambilan keputusan merasa dikenyangkan. Kita mengalami stagnasi secara meluas karena ketiadaan perspektif dan kehilangan harapan.
Memiliki utopia sebagaimana diwartakan Paskah memang seumpama memegang saham yang sedang anjlok nilainya. Tidak banyak orang berminat membelinya. Karena, memang tidak banyak orang sungguh-sungguh menghendaki perubahan. Kalau mesti berbicara tentang perubahan, itu selalu ditempatkan dalam kurung, dia menjadi perubahan yang dikurungkan, yang pada akhirnya sama dengan absennya perubahan. Paskah mengingatkan kita bahwa perubahan mesti dan bisa terjadi, selama kita menghendaki kehidupan.
Sumber: Paul Budi Kleden, Di Tebing Waktu, Ledalero, 2009






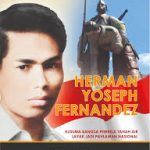



Komentar Terakhir